
Buletin Al-Islam Edisi 434
Golput haram? Itulah salah satu isu yang mengemuka baru-baru ini. Awalnya adalah Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menggagas agar MUI mengeluarkan fatwa 'haram' bagi siapa saja yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. HNW, yang mantan Presiden PKS dan kini Ketua MPR-RI, tentu punya alasan. Dalam sebuah acara dialog di sebuah televisi swasta tadi malam (TVOne, 15/12/08), HNW mengulang kembali alasan mengapa dirinya mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Ia menyatakan, berdasarkan UU yang ada, memilih memang hak. Namun, dalam konteks mewujudkan kemaslahatan, menurutnya Pemilu harus terwujud, dan itu tidak mungkin terjadi jika masyarakat ramai-ramai golput. Demikian kira-kira alasan 'rasional' HNW.
Namun, langkah ini kemudian memicu pro-kontra. Sebagian partai peserta Pemilu mendukungnya. Bahkan ada ormas Islam dan sejumlah kyai yang sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya golput. Sebagian yang lain menganggap tindakan demikian 'tidak cerdas'. Bahkan mereka menilai fatwa 'golput haram' menyesatkan serta melanggar hak warga negara dan hak asasi pemilih. "Harusnya politisi menunjukkan mereka ini layak untuk dipilih dan dipercaya. Jadi, jangan lewat fatwa, tetapi lewat karya yang konkret." Demikian komentar pengamat politik Arya Bima (13/12/2008).
Kerisauan Penikmat Demokrasi
Terlepas dari pro-kontra yang segera muncul pasca gagasan HNW ini, boleh jadi, hal itu didorong oleh kerisauan HNW terhadap maraknya golput dalam sejumlah Pilkada di berbagai daerah. Dalam Pilkada yang tiga hari sekali diselenggarakan di seluruh Indonesia, rata-rata jumlah golput di berbagai provinsi mencapai 38-40 persen. Sejumlah Pilkada pada tahun 2008 bahkan "dimenangi" oleh golput. Golput di Pilkada Jawa Barat, misalnya, mencapai 33%; Jawa Tengah 44%; Sumatera Utara 43%; Jatim (putaran I) 39,2% dan (putaran II) 46%. Angka Golput pada sejumlah Pilkada kabupaten/kota pun banyak yang mencapai 30%–40%, bahkan lebih. Gejala ini diperkirakan terus berlangsung hingga Pemilu 2009 nanti. Bahkan dalam Pilpres 2009, golput diperkirakan meningkat menjadi sekitar 40 persen, lebih tinggi daripada saat Pilpres 2004 yang 'hanya' mencapai 20 persen.
Tentu maraknya golput ini sangat merisaukan sebagian pihak yang berkepentingan dengan Pesta Demokrasi 2009. Pasalnya, Pemilu dianggap kurang sukses jika berjalan lancar tetapi minim partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab, jika golput menjadi 'pemenang', penguasa atau wakil rakyat yang terpilih tentu dianggap kurang legitimated.
Wajarlah jika kemudian sebagian politikus menggunakan berbagai cara demi mewujudkan ambisi politiknya pada Pemilu 2009. Kampanye dan iklan politik pun kemudian dilakukan dengan jor-joran. Tujuannya jelas untuk mendulang suara pemilih sebanyak-banyaknya. Namun, sekali lagi, itu tidak akan terjadi jika masyarakat banyak yang golput. Karena itulah, ada yang kemudian 'tergoda' untuk menggunakan 'bahasa agama', yakni 'fatwa' untuk kepentingan politiknya dan partainya dalam Pemilu 2009. Seolah-olah, 'perang terhadap golput' harus dilancarkan, di antaranya melalui fatwa MUI. Fatwa diharapkan menjadi 'jurus ampuh' yang bisa mencairkan kebekuan dan kejumudan sikap masyarakat terhadap demokrasi. Jadinya, 'fatwa' sekadar dijadikan alat untuk kepentingan politik pragmatis individu maupun parpol peserta Pemilu, bukan untuk kemaslahatan umat, apalagi untuk alasan-alasan yang bersifat syar'i; seperti untuk tegaknya syariah Islam di Indonesia.
Alasan di Balik Golput
Maraknya golput tentu bukan sekadar gejala kebetulan. Sebab, saat ini masyarakat tampaknya mulai 'melek politik'. Masyarakat mulai sadar, bahwa demokrasi tidak menjanjikan apa-apa; tidak kemakmuran, kesejahteraan apalagi keadilan. Demokrasi hanya menjanjikan kemiskinan dan penderitaan. Demokrasi yang katanya menempatkan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya justru sering 'mempecundangi' rakyat. Suara—bahkan jeritan hati—rakyat sering dikalahkan oleh suara para wakilnya di DPR. Misal: saat semua rakyat sepakat menolak kenaikan harga BBM, para wakilnya di DPR justru menyetujuinya. Yang menyakitkan, kebijakan menaikkan harga BBM ini, di samping diberlakukan pada saat kehidupan masyarakat yang serba sulit, juga disinyalir demi memenuhi desakan para pengusaha minyak asing di dalam negeri. Saat rakyat menolak privatisasi dan penjualan BUMN kepada pihak asing, para wakil rakyat di DPR justru semangat mendukungnya. Para wakil rakyatlah yang juga 'berjasa' dalam mengesahkan sejumlah UU yang justru berpotensi merugikan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, UU Listrik (meski kemudian dibatalkan oleh MK), dll.
Di sisi lain, penguasa yang dipilih langsung oleh rakyat juga sering lebih berpihak kepada para pemilik modal ketimbang kepada rakyat. Contoh kecil, lihatlah rakyat korban Lumpur Lapindo, yang sudah lebih dari dua tahun diabaikan begitu saja dan dibiarkan menderita. Anehnya, saat sejumlah perusahaan, termasuk Kelompok Bakrie—induk perusahaan PT Lapindo Brantas—kelimpungan diterjang krisis, Pemerintah sigap membantu meski harus mengeluarkan dana triliunan.
Singkatnya, rakyat mulai menyadari bahwa keberadaan penguasa dan wakilnya di parlemen seolah antara ada dan tidaknya sama. Karena itu, dalam pandangan mereka, memilih atau tidak memilih adalah sama saja; tidak berpengaruh terhadap nasib mereka yang semakin tragis. Itulah alasan sebenarnya di balik maraknya golput selama ini, yang diperkirakan semakin meningkat pada Pemilu 2009 nanti.
Sebuah 'Warning'
Di samping beberapa alasan di atas, maraknya golput setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama: Maraknya golput merupakan 'warning' (peringatan) bagi parpol peserta Pemilu. Beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional menunjukkan bahwa parpol saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai memahami bahwa keberadaan parpol lebih dijadikan sebagai 'kuda tunggangan' yang super komersial, siap 'direntalkan' kepada siapa saja yang ingin berkuasa—tentu yang memiliki modal (baca: uang) melimpah—dan bukan unuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kedua: alasan orang untuk golput memang beragam. Ada yang karena alasan ideologis, misalnya karena para calon/parpol peserta Pemilu tidak ada yang secara jelas dan serius memperjuangkan syariah Islam. Ada juga yang hanya karena alasan teknis, misalnya tidak terdaftar atau saat pencoblosan sedang pergi bekerja sehingga tidak memberikan suaranya. Namun, alasan teknis sekalipun sudah cukup menunjukkan bahwa masyarakat menganggap Pilkada/Pemilu bukanlah hal yang penting bagi mereka. Andaikata hal itu dinilai penting, apalagi bisa memberikan harapan untuk perbaikan, tentu masyarakat akan berduyun-duyun menuju TPS.
Lebih dari itu, Pemilu/Pilkada dalam sistem demokrasi saat ini pada faktanya telah melahirkan dampak negatif: masyarakat terkotak-kotak dan hubungan sosial menjadi renggang. Yang lebih parah, Pemilu/Pilkada bahkan sering melahirkan konflik sosial, yang tidak jarang mengarah pada bentrokan fisik dan tindakan anarkis. Sejumlah konflik berbau kekerasan di berbagai daerah Indonesia tidak jarang dipicu oleh perebutan kekuasaan pada proses Pilkada. Inilah buah nyata demokrasi!
Fatwakanlah Syariah Islam!
Jika sistem demokrasi sudah terbukti kebobrokannya dan banyak madaratnya, maka ini saja sebetulnya sudah cukup menjadi alasan, bahwa umat ini tidak layak terus-menerus berharap pada sistem demokrasi. Apalagi demokrasi sangat mudah dijadikan sebagai 'pintu masuk' oleh para pemilik modal dan para penjajah asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan milik rakyat. Bukankah leluasanya pihak asing menguasai BUMN dan sumber-sumber kekayaan alam milik rakyat adalah karena hal itu memang dilegalkan atas nama privatisasi oleh UU—yang notebene dibuat dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR—melalui proses demokrasi?
Karena itu, para tokoh, ulama, politikus dan parpol seharusnya cerdas menangkap keinginan masyarakat saat ini, yang notabene mayoritas Muslim, yakni keinginan mereka untuk hidup diatur dengan syariah Islam; bukan justru memperalat agama untuk memuaskan syahwat kekuasaan mereka, dengan alasan demi kemaslahatan umat. Padahal sudah nyata-nyata umat tidak mendapatkan kemaslahatan dari hajatan demokrasi yang hendak difatwakan.
Sementara itu, umat Islam sendiri tampak semakin teguh pilihannya untuk kembali pada syariah agama mereka. Sejumlah survei memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat pada penerapan syariah Islam dari hari ke hari makin menguat. Survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2001 menunjukkan, 57,8% responden berpendapat bahwa pemerintahan yang berdasarkan syariah Islam adalah yang terbaik bagi Indonesia. Survey tahun 2002 menunjukkan sebanyak 67% (naik sekitar 10%) berpendapat yang sama (Majalah Tempo, edisi 23-29 Desember 2002). Survey tahun 2003 menunjukkan sebanyak 75% setuju dengan pendapat tersebut.
Sebanyak 80% mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara (Hasil survey aktivis gerakan nasionalis pada 2006 di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya, Kompas, 4/3/'08).
Survey Roy Morgan Research yang dirilis Juni 2008 memperlihatkan, sebanyak 52% orang Indonesia mengatakan, syariah Islam harus diterapkan di wilayah mereka. (The Jakarta Post, 24/6/'08). Survey terbaru yang dilakukan oleh SEM Institute juga menunjukkan sekitar 72% masyarakat Indonesia setuju dengan penerapan syariah Islam.
Kenyataan inilah yang seharusnya ditangkap oleh para tokoh, ulama, politikus, ormas, dan terutama parpol peserta Pemilu.
Lebih dari sekadar keinginan mayoritas umat Islam di atas, penegakkan syariah Islam adalah kewajiban dari Allah, Pencipta alam raya ini, yang dibebankan kepada setiap Muslim.
Dengan syariah buatan Allahlah, Zat Yang Mahatahu, seharusnya negara dan bangsa ini diatur; bukan dengan aturan-aturan produk manusia yang serba lemah dan sarat kepentingan, sebagaimana selama ini terjadi. Dengan syariah Islamlah seharusnya kekayaan negeri-negeri Muslim yang luar biasa melimpah, termasuk di negeri ini, dikelola melalui tangan-tangan para pemimpin yang bertakwa dan amanah. Hanya dengan cara inilah umat Islam di negeri ini akan mampu mengakhiri kesengsaraannya.
هَـٰذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ
Inilah penjelasan yang (sejelas-jelasnya) bagi manusia supaya mereka mendapatkan peringatan dengannya. (QS Ibrahim [14]: 52).
Golput haram? Itulah salah satu isu yang mengemuka baru-baru ini. Awalnya adalah Hidayat Nur Wahid (HNW) yang menggagas agar MUI mengeluarkan fatwa 'haram' bagi siapa saja yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2009. HNW, yang mantan Presiden PKS dan kini Ketua MPR-RI, tentu punya alasan. Dalam sebuah acara dialog di sebuah televisi swasta tadi malam (TVOne, 15/12/08), HNW mengulang kembali alasan mengapa dirinya mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Ia menyatakan, berdasarkan UU yang ada, memilih memang hak. Namun, dalam konteks mewujudkan kemaslahatan, menurutnya Pemilu harus terwujud, dan itu tidak mungkin terjadi jika masyarakat ramai-ramai golput. Demikian kira-kira alasan 'rasional' HNW.
Namun, langkah ini kemudian memicu pro-kontra. Sebagian partai peserta Pemilu mendukungnya. Bahkan ada ormas Islam dan sejumlah kyai yang sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya golput. Sebagian yang lain menganggap tindakan demikian 'tidak cerdas'. Bahkan mereka menilai fatwa 'golput haram' menyesatkan serta melanggar hak warga negara dan hak asasi pemilih. "Harusnya politisi menunjukkan mereka ini layak untuk dipilih dan dipercaya. Jadi, jangan lewat fatwa, tetapi lewat karya yang konkret." Demikian komentar pengamat politik Arya Bima (13/12/2008).
Kerisauan Penikmat Demokrasi
Terlepas dari pro-kontra yang segera muncul pasca gagasan HNW ini, boleh jadi, hal itu didorong oleh kerisauan HNW terhadap maraknya golput dalam sejumlah Pilkada di berbagai daerah. Dalam Pilkada yang tiga hari sekali diselenggarakan di seluruh Indonesia, rata-rata jumlah golput di berbagai provinsi mencapai 38-40 persen. Sejumlah Pilkada pada tahun 2008 bahkan "dimenangi" oleh golput. Golput di Pilkada Jawa Barat, misalnya, mencapai 33%; Jawa Tengah 44%; Sumatera Utara 43%; Jatim (putaran I) 39,2% dan (putaran II) 46%. Angka Golput pada sejumlah Pilkada kabupaten/kota pun banyak yang mencapai 30%–40%, bahkan lebih. Gejala ini diperkirakan terus berlangsung hingga Pemilu 2009 nanti. Bahkan dalam Pilpres 2009, golput diperkirakan meningkat menjadi sekitar 40 persen, lebih tinggi daripada saat Pilpres 2004 yang 'hanya' mencapai 20 persen.
Tentu maraknya golput ini sangat merisaukan sebagian pihak yang berkepentingan dengan Pesta Demokrasi 2009. Pasalnya, Pemilu dianggap kurang sukses jika berjalan lancar tetapi minim partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab, jika golput menjadi 'pemenang', penguasa atau wakil rakyat yang terpilih tentu dianggap kurang legitimated.
Wajarlah jika kemudian sebagian politikus menggunakan berbagai cara demi mewujudkan ambisi politiknya pada Pemilu 2009. Kampanye dan iklan politik pun kemudian dilakukan dengan jor-joran. Tujuannya jelas untuk mendulang suara pemilih sebanyak-banyaknya. Namun, sekali lagi, itu tidak akan terjadi jika masyarakat banyak yang golput. Karena itulah, ada yang kemudian 'tergoda' untuk menggunakan 'bahasa agama', yakni 'fatwa' untuk kepentingan politiknya dan partainya dalam Pemilu 2009. Seolah-olah, 'perang terhadap golput' harus dilancarkan, di antaranya melalui fatwa MUI. Fatwa diharapkan menjadi 'jurus ampuh' yang bisa mencairkan kebekuan dan kejumudan sikap masyarakat terhadap demokrasi. Jadinya, 'fatwa' sekadar dijadikan alat untuk kepentingan politik pragmatis individu maupun parpol peserta Pemilu, bukan untuk kemaslahatan umat, apalagi untuk alasan-alasan yang bersifat syar'i; seperti untuk tegaknya syariah Islam di Indonesia.
Alasan di Balik Golput
Maraknya golput tentu bukan sekadar gejala kebetulan. Sebab, saat ini masyarakat tampaknya mulai 'melek politik'. Masyarakat mulai sadar, bahwa demokrasi tidak menjanjikan apa-apa; tidak kemakmuran, kesejahteraan apalagi keadilan. Demokrasi hanya menjanjikan kemiskinan dan penderitaan. Demokrasi yang katanya menempatkan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya justru sering 'mempecundangi' rakyat. Suara—bahkan jeritan hati—rakyat sering dikalahkan oleh suara para wakilnya di DPR. Misal: saat semua rakyat sepakat menolak kenaikan harga BBM, para wakilnya di DPR justru menyetujuinya. Yang menyakitkan, kebijakan menaikkan harga BBM ini, di samping diberlakukan pada saat kehidupan masyarakat yang serba sulit, juga disinyalir demi memenuhi desakan para pengusaha minyak asing di dalam negeri. Saat rakyat menolak privatisasi dan penjualan BUMN kepada pihak asing, para wakil rakyat di DPR justru semangat mendukungnya. Para wakil rakyatlah yang juga 'berjasa' dalam mengesahkan sejumlah UU yang justru berpotensi merugikan rakyat seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, UU Listrik (meski kemudian dibatalkan oleh MK), dll.
Di sisi lain, penguasa yang dipilih langsung oleh rakyat juga sering lebih berpihak kepada para pemilik modal ketimbang kepada rakyat. Contoh kecil, lihatlah rakyat korban Lumpur Lapindo, yang sudah lebih dari dua tahun diabaikan begitu saja dan dibiarkan menderita. Anehnya, saat sejumlah perusahaan, termasuk Kelompok Bakrie—induk perusahaan PT Lapindo Brantas—kelimpungan diterjang krisis, Pemerintah sigap membantu meski harus mengeluarkan dana triliunan.
Singkatnya, rakyat mulai menyadari bahwa keberadaan penguasa dan wakilnya di parlemen seolah antara ada dan tidaknya sama. Karena itu, dalam pandangan mereka, memilih atau tidak memilih adalah sama saja; tidak berpengaruh terhadap nasib mereka yang semakin tragis. Itulah alasan sebenarnya di balik maraknya golput selama ini, yang diperkirakan semakin meningkat pada Pemilu 2009 nanti.
Sebuah 'Warning'
Di samping beberapa alasan di atas, maraknya golput setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama: Maraknya golput merupakan 'warning' (peringatan) bagi parpol peserta Pemilu. Beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei nasional menunjukkan bahwa parpol saat ini mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat sudah mulai memahami bahwa keberadaan parpol lebih dijadikan sebagai 'kuda tunggangan' yang super komersial, siap 'direntalkan' kepada siapa saja yang ingin berkuasa—tentu yang memiliki modal (baca: uang) melimpah—dan bukan unuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Kedua: alasan orang untuk golput memang beragam. Ada yang karena alasan ideologis, misalnya karena para calon/parpol peserta Pemilu tidak ada yang secara jelas dan serius memperjuangkan syariah Islam. Ada juga yang hanya karena alasan teknis, misalnya tidak terdaftar atau saat pencoblosan sedang pergi bekerja sehingga tidak memberikan suaranya. Namun, alasan teknis sekalipun sudah cukup menunjukkan bahwa masyarakat menganggap Pilkada/Pemilu bukanlah hal yang penting bagi mereka. Andaikata hal itu dinilai penting, apalagi bisa memberikan harapan untuk perbaikan, tentu masyarakat akan berduyun-duyun menuju TPS.
Lebih dari itu, Pemilu/Pilkada dalam sistem demokrasi saat ini pada faktanya telah melahirkan dampak negatif: masyarakat terkotak-kotak dan hubungan sosial menjadi renggang. Yang lebih parah, Pemilu/Pilkada bahkan sering melahirkan konflik sosial, yang tidak jarang mengarah pada bentrokan fisik dan tindakan anarkis. Sejumlah konflik berbau kekerasan di berbagai daerah Indonesia tidak jarang dipicu oleh perebutan kekuasaan pada proses Pilkada. Inilah buah nyata demokrasi!
Fatwakanlah Syariah Islam!
Jika sistem demokrasi sudah terbukti kebobrokannya dan banyak madaratnya, maka ini saja sebetulnya sudah cukup menjadi alasan, bahwa umat ini tidak layak terus-menerus berharap pada sistem demokrasi. Apalagi demokrasi sangat mudah dijadikan sebagai 'pintu masuk' oleh para pemilik modal dan para penjajah asing untuk menguasai sumber-sumber kekayaan milik rakyat. Bukankah leluasanya pihak asing menguasai BUMN dan sumber-sumber kekayaan alam milik rakyat adalah karena hal itu memang dilegalkan atas nama privatisasi oleh UU—yang notebene dibuat dan disahkan oleh Pemerintah dan DPR—melalui proses demokrasi?
Karena itu, para tokoh, ulama, politikus dan parpol seharusnya cerdas menangkap keinginan masyarakat saat ini, yang notabene mayoritas Muslim, yakni keinginan mereka untuk hidup diatur dengan syariah Islam; bukan justru memperalat agama untuk memuaskan syahwat kekuasaan mereka, dengan alasan demi kemaslahatan umat. Padahal sudah nyata-nyata umat tidak mendapatkan kemaslahatan dari hajatan demokrasi yang hendak difatwakan.
Sementara itu, umat Islam sendiri tampak semakin teguh pilihannya untuk kembali pada syariah agama mereka. Sejumlah survei memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat pada penerapan syariah Islam dari hari ke hari makin menguat. Survei PPIM UIN Syarif Hidayatullah tahun 2001 menunjukkan, 57,8% responden berpendapat bahwa pemerintahan yang berdasarkan syariah Islam adalah yang terbaik bagi Indonesia. Survey tahun 2002 menunjukkan sebanyak 67% (naik sekitar 10%) berpendapat yang sama (Majalah Tempo, edisi 23-29 Desember 2002). Survey tahun 2003 menunjukkan sebanyak 75% setuju dengan pendapat tersebut.
Sebanyak 80% mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara (Hasil survey aktivis gerakan nasionalis pada 2006 di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya, Kompas, 4/3/'08).
Survey Roy Morgan Research yang dirilis Juni 2008 memperlihatkan, sebanyak 52% orang Indonesia mengatakan, syariah Islam harus diterapkan di wilayah mereka. (The Jakarta Post, 24/6/'08). Survey terbaru yang dilakukan oleh SEM Institute juga menunjukkan sekitar 72% masyarakat Indonesia setuju dengan penerapan syariah Islam.
Kenyataan inilah yang seharusnya ditangkap oleh para tokoh, ulama, politikus, ormas, dan terutama parpol peserta Pemilu.
Lebih dari sekadar keinginan mayoritas umat Islam di atas, penegakkan syariah Islam adalah kewajiban dari Allah, Pencipta alam raya ini, yang dibebankan kepada setiap Muslim.
Dengan syariah buatan Allahlah, Zat Yang Mahatahu, seharusnya negara dan bangsa ini diatur; bukan dengan aturan-aturan produk manusia yang serba lemah dan sarat kepentingan, sebagaimana selama ini terjadi. Dengan syariah Islamlah seharusnya kekayaan negeri-negeri Muslim yang luar biasa melimpah, termasuk di negeri ini, dikelola melalui tangan-tangan para pemimpin yang bertakwa dan amanah. Hanya dengan cara inilah umat Islam di negeri ini akan mampu mengakhiri kesengsaraannya.
هَـٰذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ
Inilah penjelasan yang (sejelas-jelasnya) bagi manusia supaya mereka mendapatkan peringatan dengannya. (QS Ibrahim [14]: 52).
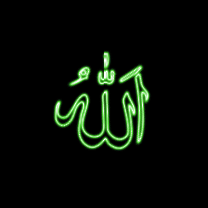









.jpg)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar